Pernah dalam sebuah lomba renang saya
menemui anak saya menangis karena gagal. Sebenarnya gagal dalam sebuah
perlombaan bukan hal yang baru baginya, karena
mental sportifitasnya sudah terasah dengan baik. Namun kali itu ia
menangis karena gagal melakukan yang terbaik.
Mengapa? Sebenanrya lomba itu bukan untuk perenang, tetapi penyelam. Dia
gagal karena tidak bisa berenang dengan menggunakan snorkel. Persiapannya tidak cukup dan ternyata peserta
wajib menggunakannya.
Secara enteng, saya berkomentar,”Apa susahnya
pakai snorkel, kan lebih enak, tidak perlu ambil nafas.” Namun setelah melihat
bagaiamana yang seharusnya, barulah saya memahami kesulitannya. Anak-anak ini
akan memakai snorkel-nya di atas saat start. Kemudian begitu mulai mereka
melompat ke air secara otomatis pipa snorkel akan ikut terendam. Begitu mereka
naik di permukaan, air di dalam pipa tersebut harus mereka semburkan terlebih
dahulu supaya pipa kosong dan perenang atau tepatnya penyelam bisa leluasa
berenang dengan bernafas melalui mulutnya. Itu satu kesulitan yang tak
terbayangkan bagi saya yang sekedar “penonton” dan “komentator” di pinggir
kolam.
Hal ini cukup menyentak diri saya,
teringat bagaimana kita sebagai orangtua terkadang bersikap salah terhadap
kesulitan belajar anak-anak. Di kelas Kumon, terkadang kita temui anak-anak
yang kesulitan di level dasar yang mungkin bagi orang dewasa sesuatu yang
sepele. Kita tidak bisa memahami kesulitannya, karena tidak berdiri pada posisi
mereka. Begitu mudah bagi kita berkomentar ,”Apa susahnya?!”. Dan sikap ini justru menjadikan mereka tidak
termotivasi untuk mau berusaha lebih baik lagi.
Empati bisa timbul secara tulus, bila
kita mau berdiri di tempat yang sama dengan anak-anak dan mengerti betul rasa
sulitnya. Dengan demikian, kita dapat membantu mereka melewati kesuitannya.
Pendampingan seperti ini akan jauh lebih berarti dibandingkan dengan sekedar
komentar yang penuh kritikan.
Di kelas Kumon, pernah seorang siswa
mengatakan, “Ibu, yang ini susah,” ketika ia mengerjakan hitungan pengurangan
di level A. Saya tidak segera mengatakan bahwa sebenarnya itu mudah, tetapi hanya
menjawab,”Oke, sekarang kerjakan saja soal yang menurutmu mudah. Begitu susah,
nanti Ibu temani.” Ajaibnya, sampai selesai ia tidak menemui saya. Waktu akan
pulang saya bertanya padanya,”Lho, mana tadi yang susah?” Dengan senyum siswa
tersebut memnjawab,”Ternyata aku bisa.”
Saya yakin, sebenarnya siswa ini mampu
menyelesaikan hitungan tersebut dengan baik. Namun ia merasa tenang ketika saya sudah berjanji akan memenemaninya bila ia
kesuitan. Rasa tenang ini membuatnya justru bisa melewatinya sendiri. Dan tentu
saja hal ini memberikan sense of
achievement baginya. Pelajaran berharga tentu saja. Saya ingin semua anak
bisa mengalami dan merasakan kepuasan ini, rasa “aku bisa!”.




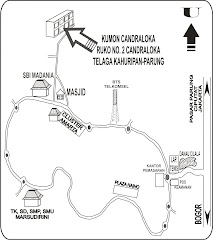


No comments:
Post a Comment